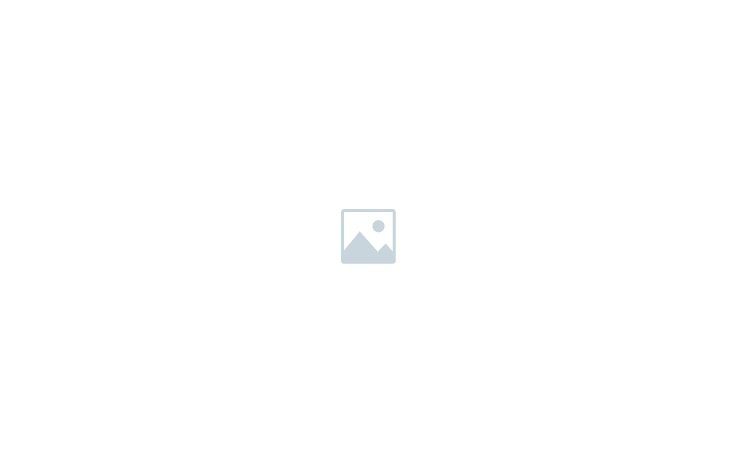Di banyak tempat, kain bekas berakhir sebagai limbah. Disimpan terlalu lama, lalu dibuang saat dianggap tidak berguna lagi. Namun bagi Ardhiana Malrasari, kain bekas justru membuka jalan yang berbeda bukan hanya tentang produk upcycle, tetapi tentang bagaimana ruang kerja bisa menjadi tempat yang lebih adil bagi semua orang.
Melalui D’Belel , usaha tas upcycle yang ia rintis dari rumah, Ardhiana pelan-pelan membangun ekosistem kerja inklusif dengan melibatkan karyawan penyandang disabilitas dalam proses produksi. Bukan sebagai simbol, bukan pula sekadar narasi sosial, melainkan sebagai bagian nyata dari rantai kerja sehari-hari.
“Buat saya, yang penting itu bukan sempurna atau rapi. Tapi bagaimana mereka bisa terlibat dan merasa punya peran,” ujar Ardhiana.
Keputusan itu lahir bukan dari konsep besar tentang inklusi, melainkan dari kegelisahan sederhana. Di sekitarnya, ia melihat banyak orang dengan keterbatasan fisik atau intelektual yang sulit mendapat ruang kerja, bukan karena tak mampu, tetapi karena tak pernah diberi kesempatan mencoba.
Belajar Bersama, Bekerja Tanpa Standar yang Meminggirkan

Foto:Dok Pribadi/natera
Ardhiana tidak memulai D’Belel dengan rencana bisnis yang matang. Awalnya, ia hanya ingin memanfaatkan seragam kerja bekas yang menumpuk di rumah. Seragam lama suaminya, pakaian yang tak lagi terpakai, hingga kain batik ciprat dari komunitas penyandang disabilitas ia olah perlahan menjadi tas dan aksesori.
Dari proses itu, ia menyadari satu hal penting: produksi upcycle membutuhkan kesabaran, ketelitian, dan detail kerja keterampilan yang justru dimiliki banyak penyandang disabilitas jika diberi ruang belajar yang tepat.
Ia mulai melibatkan mereka dalam proses awal produksi. Mulai dari memilah kain, melepas kancing, mendedel benang, hingga memisahkan label dan aksesoris kecil. Pekerjaan yang sering dianggap remeh justru menjadi pintu masuk bagi keterlibatan mereka.
“Awalnya memang lama. Tapi itu bukan soal cepat atau lambat. Yang penting prosesnya,” kata Ardhiana.
Ia tidak menetapkan target produksi ketat. Tidak ada tekanan waktu yang memaksa. Setiap orang bekerja sesuai ritmenya. Jika satu tas butuh dua hari, maka dua hari itulah yang diterima sebagai bagian dari proses.
Pendekatan ini membuat ruang kerja D’Belel terasa berbeda. Tidak hiruk-pikuk, tidak kompetitif. Lebih menyerupai ruang belajar bersama, tempat kesalahan bukan sesuatu yang harus disembunyikan, melainkan diperbaiki secara perlahan.
Ardhiana menyadari bahwa tantangan terbesarnya bukan pada teknis produksi, melainkan pada stigma. Masih banyak orang yang memandang pekerja penyandang disabilitas sebagai “tidak efisien” atau “merepotkan”. Ia justru melihat sebaliknya: dengan pendekatan yang manusiawi, mereka bisa bekerja dengan konsistensi tinggi dan loyalitas yang kuat.
Inklusi yang Bertumbuh dari Kepercayaan, Bukan Kasihan
Bagi Ardhiana, mempekerjakan karyawan penyandang disabilitas bukan soal belas kasihan. Ia menolak narasi yang menempatkan mereka sebagai objek bantuan. Di D’Belel, setiap orang punya peran yang jelas dan dihargai sebagai pekerja, bukan sebagai “yang dibantu”.
“Kalau kita dari awal menganggap mereka tidak mampu, ya sampai kapan pun tidak akan berkembang,” ujarnya.
Perlahan-lahan, kepercayaan itu menghasilkan hasil. Produk D’Belel tidak hanya diterima pasar lokal, tetapi juga menarik perhatian konsumen dari kota-kota besar seperti Jakarta, yang sudah terbiasa dengan produk berkonsep menginginkan dan inklusi sosial.
Namun perjalanan ini tidak selalu mulus. Ardhiana mengakui bahwa menjual produk upcycle berbasis sosial membutuhkan edukasi panjang. Banyak calon pembeli mengekstrak harga, mengekstrak kualitas, bahkan bertanya mengapa barang bekas bisa bernilai tinggi.
Kisah dibalik produk menjadi penting. Setiap tas tidak hanya membawa fungsi, tetapi juga narasi tentang limbah yang menyelamatkan dan tentang tangan-tangan yang mengerjakannya dengan penuh kesabaran.
Ardhiana juga mulai berbagi pengalamannya dalam berbagai pelatihan. Ia diundang ke beberapa kota untuk mengajarkan konsep upcycle sekaligus membuka diskusi tentang kerja inklusif. Dari pelatihan itu, muncul komunitas-komunitas baru yang mulai melibatkan ibu rumah tangga dan penyandang disabilitas dalam produksi kerajinan berbasis limbah.
Baginya, keberhasilan bukan diukur dari seberapa besar usahanya berkembang, melainkan dari seberapa banyak ruang kerja yang bisa menjadi lebih manusiawi.
“Kalau satu orang saja merasa termotivasi lewat pekerjaannya, itu sudah cukup,” katanya.
Kisah Ardhiana Malrasari menunjukkan bahwa inklusi tidak selalu lahir dari kebijakan besar atau proyek formal. Ia bisa tumbuh dari rumah, dari kain bekas, dan dari keberanian untuk mempercayai orang yang sering dianggap tidak mampu.
Di tangan Ardhiana, limbah tak hanya berubah menjadi nilai produk. Ia menjelma menjadi jembatan menghubungkan kesempatan kerja dengan martabat, dan membuktikan bahwa ruang inklusif dapat dibangun dari langkah kecil yang konsisten.