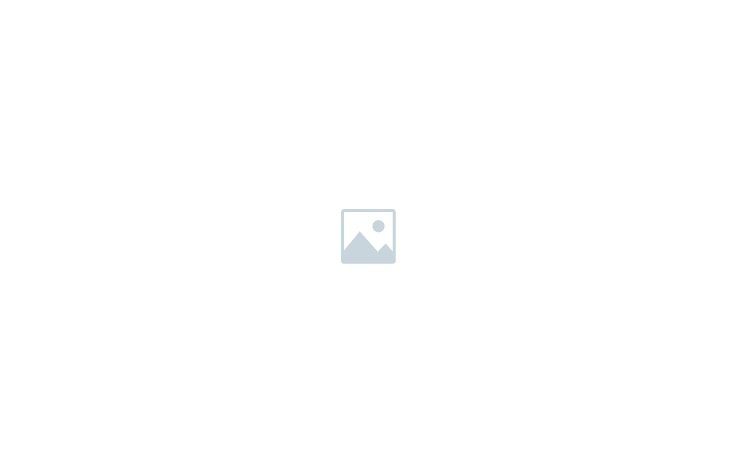Foto: Dok Pribadi/Natera
Kota Batu – Halo Naters! Di tengah kebiasaan masyarakat yang menganggap tisu sebagai benda wajib di meja makan, sedikit yang menyadari bahwa produk sekali pakai ini menyimpan jejak ekologis panjang. Tisu berasal dari serat kayu, diproduksi melalui proses intensif energi, dan hampir selalu berakhir di tempat sampah setelah satu kali pakai. Di Indonesia, lonjakan industri kuliner ikut menyumbang borosnya konsumsi tisu, yang berarti penebangan pohon tambahan dan timbunan limbah organik di tempat pembuangan akhir (TPA).
Namun di Kota Batu, ada sebuah kafe yang memilih jalan berbeda. Tidak ada gulungan tisu di atas meja. Sebagai gantinya, pengunjung disambut selembar serbet kain yang terlipat rapi. Bagi sebagian orang, ini terasa asing. Bagi yang lain, ini menjadi pengalaman yang mengubah cara pandang.
Bukan Menghilangkan, Tapi Mengganti
Ismi menegaskan, kafenya tidak sekadar “melarang” penggunaan tisu. Yang dilakukan adalah mengganti barang sekali pakai dengan alternatif yang bisa digunakan berulang kali. Tisu digantikan dengan kain serbet. Apabila ada yang ingin mengunakan atau meminta tisu bisa langsung minta ke karyawan, langkah ini untuk mengurangi penggunaan tisu. Serbet ini dicuci dan digunakan kembali, bukan dibuang setelah satu kali pakai.
“Kami tidak semata-mata tidak menyediakan tisu, tapi kami punya barang pengganti supaya tidak sekali pakai,” katanya.
Langkah ini muncul dari pengalaman langsung melihat bagaimana tisu digunakan secara berlebihan. Dalam situasi kafe yang ramai, tisu sering diambil dalam jumlah banyak bahkan untuk keperluan yang sebenarnya bisa dilakukan tanpa tisu.
Tisu Masih Ada, Tapi Berasal dari Bambu
Retrorika tidak sepenuhnya menghapus penggunaan tisu. Di ruang paling personal seperti toilet, tisu tetap disediakan, namun dengan pilihan material yang berbeda: tisu berbahan bambu. Keputusan ini lahir dari kesadaran bahwa tidak semua kebutuhan bisa digantikan, tetapi tetap bisa dikendalikan agar dampak lingkungannya lebih kecil. Ismi menjelaskan bahwa tisu putih konvensional umumnya berasal dari pohon kayu yang proses produksinya panjang dan intensif sumber daya.
“Kalau tisu putih yang biasa kita pakai itu dari pohon. Prosesnya butuh pemutih banyak, zat kimia banyak, dan airnya juga besar,” katanya.
Sebaliknya, bambu dipilih karena merupakan fast growing species tanaman yang tumbuh cepat dan dapat dipanen tanpa merusak ekosistem hutan dalam jangka panjang.
Di tengah budaya konsumsi cepat dan serba praktis, pilihan kecil seperti mengganti tisu pohon dengan tisu bambu mungkin tampak sepele. Namun, di Retrorika, keputusan itu menjadi bagian dari narasi yang lebih besar: mengurangi jejak ekologis tanpa mengorbankan kebutuhan dasar manusia. Sebuah kompromi yang sadar, bukan sekadar simbolik.
Bijak Menggunakan, Bukan Anti Tisu
Bagi Retrorika, persoalan tisu bukan semata ada atau tidak ada, melainkan bagaimana kebiasaan menggunakannya bisa diubah. Ismi menilai, di ruang publik seperti kafe, penggunaan tisu kerap lepas kendali karena dianggap barang murah dan selalu tersedia. Akibatnya, satu meja bisa menghabiskan beberapa lembar tisu hanya untuk mengelap air atau sisa makanan kecil.
“Kalau sudah di ruang publik, customer itu bebas ambil. Mau ngelap air pun pakai tisu, bahkan ambil banyak,” ujar Ismi.
Pengalaman itulah yang mendorong Retrorika membatasi keberadaan tisu di meja makan. Bukan untuk melarang, melainkan memberi jeda agar orang berpikir ulang sebelum mengambilnya.
Ketika tisu tidak lagi langsung tersedia, pengunjung dihadapkan pada pilihan lain yang lebih berkelanjutan, seperti kain serbet yang bisa digunakan berulang kali. Dalam praktiknya, tisu tetap ada dan bisa diminta jika memang dibutuhkan. Namun, posisinya tidak lagi sebagai barang utama yang diambil tanpa sadar, melainkan sebagai alternatif terakhir.
Di tengah krisis lingkungan dan meningkatnya timbulan sampah, langkah kecil seperti mengurangi pemakaian tisu berlebih menjadi bagian dari perubahan yang lebih besar. Retrorika menunjukkan bahwa hidup ramah lingkungan tidak harus dimulai dari sikap ekstrem, melainkan dari kesadaran sederhana. Menggunakan seperlunya, bukan sebanyak-banyaknya.
Pada akhirnya, selembar tisu yang kita sobek dengan mudah menyimpan cerita panjang tentang pohon yang ditebang, air yang dihabiskan, dan bahan kimia yang dilepaskan ke lingkungan. Industri tisu berbahan kayu tidak hanya bergantung pada eksploitasi hutan, tetapi juga meninggalkan jejak ekologis dalam proses pemutihan dan produksinya. Ketika tisu digunakan berlebihan dan langsung dibuang setelah sekali pakai, siklus perusakan itu terus berulang tanpa disadari.
Pengalaman di Retrorika mengingatkan bahwa perubahan tidak selalu harus dimulai dari kebijakan besar atau teknologi mahal. Mengganti tisu dengan kain serbet, memilih tisu bambu di ruang yang memang membutuhkannya, serta menggunakan tisu secara bijak adalah bentuk perlawanan sunyi terhadap budaya boros sekali pakai.