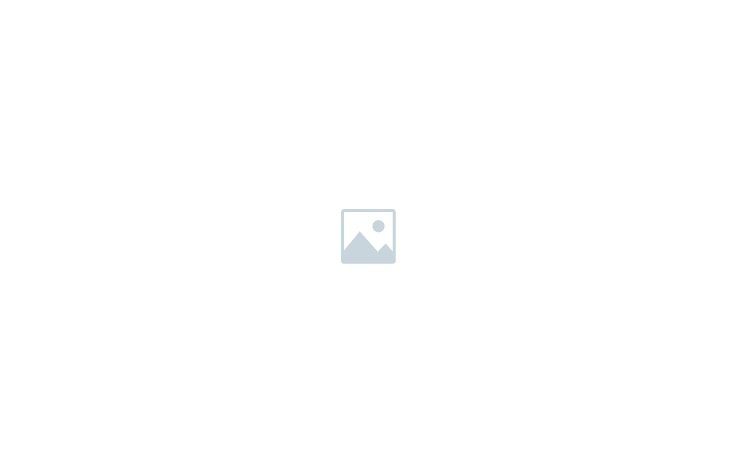Neters, tau gak si? Kalau abu sisa pembakaran selama ini dianggap tak bernilai. Debu yang menempel di tangan, sisa yang ingin segera disingkirkan. Namun di sebuah desa di Blitar, abu justru menjadi pintu masuk perubahan bukan hanya soal material bangunan, tapi tentang bagaimana warga, terutama ibu-ibu rumah tangga, mulai melihat limbah sebagai peluang ekonomi.
Sunalis, pengelola sampah desa yang lebih dulu dikenal karena eksperimennya mengolah abu menjadi material bangunan alternatif, kini melangkah lebih jauh. Setelah bertahun-tahun berkutat dengan persoalan teknis limbah, ia menyadari satu hal: perubahan lingkungan tidak akan bertahan lama jika tidak diikuti perubahan ekonomi warga.
“Kalau cuma soal sampah, orang bisa patuh sebentar. Tapi kalau sampah itu bisa bantu dapur tetap ngebul, ceritanya jadi beda,” ujar Sunalis
Dari pemikiran itulah rencana pemberdayaan mulai dirangkai melibatkan warga secara langsung dalam produksi kerajinan daur ulang berbasis desa.
Ketika Limbah Menjadi Kerja Kolektif Warga

Di desa tempat Sunalis tinggal, sebagian besar ibu rumah tangga memiliki waktu luang di sela aktivitas domestik. Namun peluang kerja terbatas. Banyak dari mereka tidak memiliki akses ke modal, pelatihan, atau jaringan pasar. Di sisi lain, desa ini justru memiliki satu “bahan baku” melimpah: limbah.
Abu pembakaran, plastik sisa rumah tangga, hingga residu non-organik yang sulit dijual, selama ini hanya ditumpuk atau dibakar. Sunalis melihat celah di sana. Ia mulai mengajak beberapa ibu untuk sekadar mencoba mencetak pot tanaman sederhana dari campuran abu, membuat ornamen kecil, hingga produk kerajinan yang tidak menuntut alat rumit.
Pendekatannya tidak menggurui. Tidak ada pelatihan formal di awal. Ia memulai dari praktik, dari coba-coba, dari kesalahan yang diperbaiki bersama. Ruang produksi pun sederhana teras rumah, balai kecil desa, atau halaman TPS.
“Biar mereka pegang langsung bahannya. Dari situ biasanya muncul rasa percaya diri,” kata Sunalis.
Perlahan, proses ini mengubah relasi warga dengan limbah. Sampah tidak lagi hanya urusan Sunalis sebagai pengelola. Ia menjadi urusan bersama. Ibu-ibu mulai memilah, menyimpan, bahkan meminta jenis limbah tertentu karena tahu akan dipakai untuk produksi.
Dari sinilah ekosistem kecil mulai terbentuk: ada yang fokus mencetak, ada yang merapikan, ada yang mengeringkan, dan ada pula yang mengemas. Skala produksinya memang belum besar. Namun nilainya bukan hanya pada jumlah produk, melainkan pada keterlibatan warga yang sebelumnya tak tersentuh aktivitas ekonomi hijau.
Ekonomi Hijau dari Desa, Bukan Pabrik Besar
Bagi Sunalis, pemberdayaan bukan tentang menjadikan semua orang pengusaha. Ia lebih tertarik membangun sistem yang bisa dijalankan bersama dan tumbuh perlahan. Produk kerajinan dari limbah ini tidak ditargetkan masuk pasar besar. Fokusnya justru pada kebutuhan lokal: pot tanaman untuk warga, paving sederhana untuk halaman, ornamen desa, hingga pesanan kecil dari komunitas lingkungan.
Model ini membuat ibu-ibu tidak terbebani target berlebihan. Mereka bekerja sesuai waktu dan kemampuan. Upah dibagi berdasarkan hasil produksi, bukan jam kerja. Pola ini memberi ruang fleksibel tanpa menambah tekanan domestik.
Yang lebih penting, proses ini menumbuhkan rasa memiliki. Warga tidak lagi sekadar “membantu” program Sunalis. Mereka menjadi bagian dari rantai nilai. Limbah yang mereka hasilkan kembali dalam bentuk produk yang punya fungsi dan nilai ekonomi.
Dampak sosialnya terasa pelan-pelan. Percakapan warga berubah. Dari yang awalnya bertanya “sampah ini mau dibuang ke mana?” menjadi “ini bisa dibuat apa lagi?” Kesadaran lingkungan tumbuh seiring manfaat ekonomi yang nyata.
Sunalis menyadari tantangan masih besar. Standar kualitas harus dijaga. Pasar masih terbatas. Modal pengembangan belum tersedia. Namun ia tidak terburu-buru. Baginya, keberlanjutan lebih penting daripada pertumbuhan cepat.
“Kalau warga sudah terbiasa bekerja bareng, nanti usahanya bisa menyusul,” katanya.
Rencana ke depan, Sunalis ingin membentuk kelompok produksi resmi berbasis desa. Bukan untuk mengejar skala industri, tetapi agar warga punya posisi tawar, akses pelatihan, dan kemungkinan kolaborasi dengan pihak luar. Ia membayangkan desa sebagai simpul kecil ekonomi hijau tempat limbah tidak berakhir, tetapi berputar.
Kisah Sunalis menunjukkan bahwa inovasi lingkungan tidak selalu tentang teknologi canggih. Terkadang, ia lahir dari abu, dari tangan-tangan warga, dan dari kesabaran membangun kepercayaan. Di desa ini, pemberdayaan tidak datang sebagai program besar, melainkan sebagai kerja bersama pelan, sederhana, dan berakar pada kehidupan sehari-hari.
Dari limbah yang dulu dianggap beban, kini tumbuh harapan baru. Bukan hanya tentang lingkungan yang lebih bersih, tetapi tentang warga yang lebih berdaya.