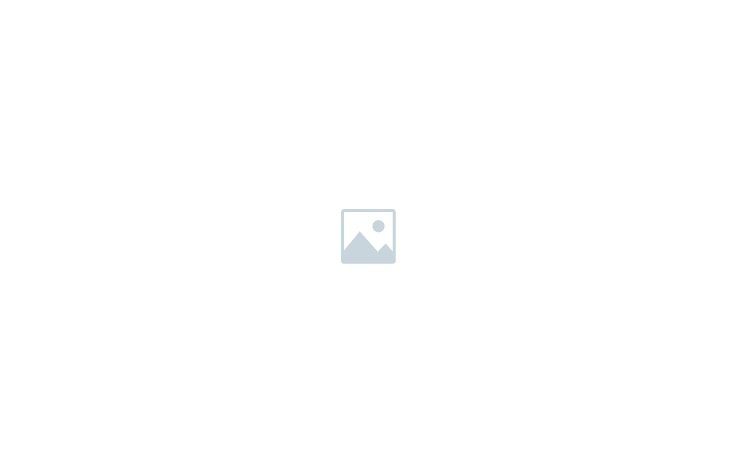Percakapan sore itu terdengar berantakan, penuh tawa, jeda, dan potongan kalimat yang saling tumpang tindih. Namun dari rekaman itulah, satu benang merah muncul: kegelisahan tentang lingkungan yang tak berhenti di ruang kelas.
Firman, CEO Capung Lam, mengingat kembali awal mula semuanya bermula dari praktikum kampus. Ia dan timnya merancang media sederhana yang kelak bernama Natera, sebuah website yang mereka bayangkan menjadi ruang berbagi cerita lingkungan.
“Praktikum dua, yang dimana kita rencananya, apakah rencananya kita membangun satu media,” ujar Firman. Media itu mereka niatkan untuk membahas isu lingkungan secara ringan, dekat dengan keseharian, dan bisa diakses siapa saja.
Pertemuan dengan Capung Lam bermula dari rasa ingin tahu. Firman dan timnya bertemu langsung dengan pihak lapangan, merekam percakapan, lalu mengolahnya menjadi artikel. Semua bermula dari upaya belajar, bukan target bisnis.
Namun realitas lapangan segera mematahkan idealisme awal. Ketika Firman mencoba masuk ke pengelolaan sampah organik lewat budidaya cacing, jalannya tak semulus teori. Selama lebih dari setahun, usaha itu justru merugi puluhan juta rupiah.
“Ternyata nggak semudah itu main sampah organik,” katanya. Bau, komplain warga, cuaca, hingga hasil yang tak sebanding dengan biaya membuatnya berhenti sejenak dan berpikir ulang.
Ia mulai memahami satu hal penting: ide yang tak pernah terealisasi hanya akan menjadi sampah baru. Dari situ, fokus Capung Lam perlahan bergeser. Bukan lagi sekadar mengolah limbah, tetapi membangun sistem yang bisa bertahan.
Minyak jelantah menjadi pintu masuk berikutnya. Dari dapur rumah tangga, limbah itu dikumpulkan, ditukar, dan dikelola. Di Malang, Capung Lam membuka lebih dari sepuluh depo minyak jelantah dengan skema kolektif ibu-ibu sebagai penggerak utama.
“Satu liter minyak bisa ditukar jadi minyak baru,” jelas Kak Adel, tim marketing Capung Lam. Skema ini menjawab dua masalah sekaligus: saluran air yang mampet dan potensi ekonomi yang terbuang.
Namun edukasi tetap menjadi tantangan terbesar. Banyak warga awalnya mengira program ini sekadar kampanye sesaat. Capung Lam harus datang berkali-kali, membangun kepercayaan, dan menunjukkan konsistensi.
Kesadaran itu membuat Capung Lam mulai serius membangun sisi edukasi. Firman menyadari, tanpa pemahaman, perubahan hanya akan berhenti di acara seremonial.
“Kalau kita edukasi tapi nggak diterapkan di rumah, ya percuma,” ujarnya.
Dari sana, lahirlah gagasan Capung Lam Academy. Edukasi tak lagi berhenti di webinar, tetapi dilanjutkan dengan pendampingan, workshop, dan rencana edutek berbasis pertanian dan peternakan berkelanjutan.
Capung Lam juga masuk ke sekolah dasar. Metodenya jauh dari ceramah. Anak-anak diajak bermain, menepuk tangan, dan mengenali warna tempat sampah. Hijau untuk organik, kuning untuk anorganik, merah untuk residu.
“Kalau anak kecil dikasih materi berat, nggak akan nangkep,” kata Kak Adel. Games menjadi bahasa yang mereka pahami.
Hasilnya mulai terlihat. Anak-anak tak hanya tahu cara memilah sampah, tetapi juga memahami bahwa sampah anorganik punya nilai ekonomi. Mereka menjadi lebih rajin memilah, bukan sekadar membuang.
Di luar sekolah, Capung Lam membangun komunitas Eco-Friend, ruang aman bagi anak muda untuk berdiskusi soal lingkungan. Dari obrolan sampah desa, peluang kerja di industri hijau, hingga kegiatan lapangan seperti fun run dan field trip.
Komunitas ini tumbuh sebagai kanal belajar dua arah. Capung Lam mendengar langsung keresahan anak muda, sementara anggota komunitas menemukan pintu masuk konkret untuk berbuat.
Bagi Firman, semua perjalanan ini bermuara pada satu visi besar. Ia ingin menyatukan dampak lingkungan dan sosial. Latar belakang keluarganya membuat isu inklusivitas, khususnya bagi anak berkebutuhan khusus, menjadi bagian dari mimpi besarnya.
“Manusia dan alam itu seimbang,” katanya. Merawat lingkungan tanpa membangun manusianya hanya akan menciptakan lingkaran masalah baru.
Ke depan, Capung Lam menargetkan pensiunan sebagai kelompok utama edukasi. Mereka melihat potensi besar dari rumah tangga, dari dapur hingga pekarangan, untuk mengelola limbah menjadi nilai ekonomi.
Perjalanan Capung Lam menunjukkan bahwa perubahan lingkungan jarang lahir dari jalan lurus. Ia tumbuh dari kegagalan, trial-error, dan keberanian mengubah arah. Dari praktikum kampus, Capung Lam kini perlahan merangkai ekosistem belajar yang berakar di kehidupan sehari-hari.