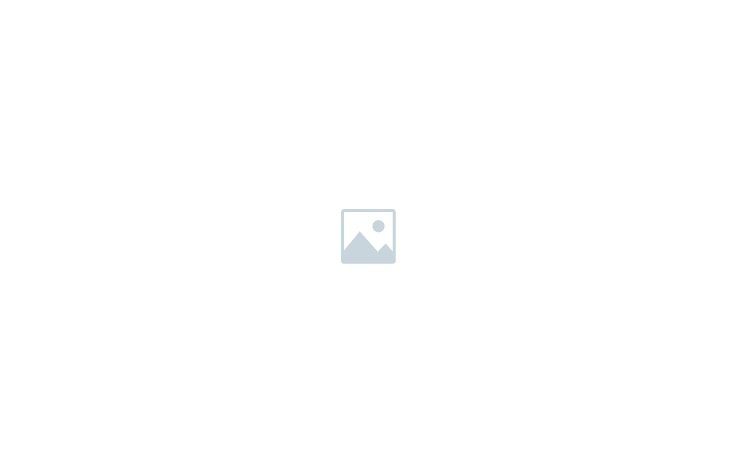Halo Neters, pernah kepikiran nggak kalau di balik sepiring nasi goreng yang habis disantap, ada jejak lain yang tertinggal jejak karbon? Bukan cuma dari kendaraan yang mengantar bahan makanan atau listrik yang menyalakan dapur, tapi juga dari sisa yang sering kita anggap sepele. Di sebuah kafe yang pelan-pelan mengubah cara memandang sisa makanan, cerita itu mulai dirangkai. Retro Farm, sebuah inisiatif yang lahir dari dapur, tidak berhenti pada urusan rasa. Ia bergerak lebih jauh: merawat sisa, menghitung dampak, lalu mengajak pengunjung ikut bertanggung jawab.
“Kami sedang menuju low carbon brand movement. Jadi kami berusaha meminimalisir carbon footprint dari makanan,” ujar pengelola Retro Farm dalam sebuah sesi wawancara. Kalimat itu bukan jargon kosong. Di sini, sisa makanan bukan akhir dari proses, tapi awal dari sebuah siklus baru yang lebih panjang.
Setiap malam, sisa nasi, lauk, dan makanan yang tak habis tidak langsung dibuang ke tong sampah. Semuanya dikumpulkan, ditimbang, dan dicatat. Pagi harinya, sisa tersebut dikirim ke peternak mitra. Namun prosesnya tidak berhenti di sana. Makanan itu tidak langsung diberikan ke ternak, melainkan dibiarkan beberapa hari hingga membusuk secara alami dan menghasilkan belatung sumber protein tinggi bagi unggas.
“Tidak langsung dikasihkan. Dibiarkan dulu supaya ada belatungnya. Itu protein sempurna untuk unggas,” jelasnya.
Sementara itu, sisa yang tidak cocok untuk pakan seperti kulit buah, daun, dan sisa bumbu dapur dialihkan ke jalur berbeda: dekomposer, lalu diolah menjadi kompos.
Di titik ini, Retro Farm tidak hanya bicara soal pengurangan sampah. Mereka mulai bicara soal menghitung.
Dapur, Peternakan, dan Angka yang Mulai Diperhitungkan

Retro Farm mulai mendata hal-hal yang selama ini sering luput dari perhatian: berapa banyak sampah makanan yang dihasilkan, berapa sisa daun dan organik, hingga berapa plastik yang masih tersisa. Semua dicatat secara rutin setiap bulan. Bukan untuk laporan formal atau pencitraan, melainkan untuk satu tujuan jangka panjang menghitung jejak karbon dari makanan.
“Carbon footprint itu bukan cuma dari bensin atau solar. Dari makanan ternyata juga ada jejak karbonnya,” tuturnya. Dari kesadaran inilah gagasan carbon tagging muncul.
Ke depan, setiap menu direncanakan memiliki informasi jejak karbon yang dihitung dalam satuan CO₂ equivalent (CO₂e). Misalnya, satu porsi nasi goreng menghasilkan sekitar 0,5 kilogram CO₂e. Angka ini tidak berhenti sebagai informasi semata. Pengunjung akan diberi pilihan, mau atau tidak menebus jejak karbon dari makanan yang mereka konsumsi.
Skemanya dibuat sederhana. Bukan kewajiban, bukan pajak, melainkan pilihan sadar. Dana yang terkumpul dari kompensasi ini akan dialokasikan untuk penanaman pohon melalui kolaborasi dengan Bumi Baik, sebuah inisiatif yang fokus pada restorasi dan penanaman pohon.
“Kompensasi jejak karbon itu sebenarnya menanam pohon. Nanti dikumpulkan, lalu kita tanam,” katanya.
Model ini terinspirasi dari praktik carbon offset pada sektor transportasi seperti tiket kereta atau penerbangan namun diterjemahkan ke konteks dapur dan makanan sehari-hari. Pendekatan yang masih jarang disentuh oleh pelaku UMKM, padahal kontribusinya sangat besar.
“UMKM itu sekitar 70 persen menopang ekonomi nasional. Kalau ada yang mulai, semoga bisa menginspirasi,” ujarnya.
Yang menarik, sistem ini tidak menunggu segalanya sempurna. Perhitungan listrik, bahan bakar, hingga rantai pasok masih terus dikembangkan. Namun langkah awalnya sudah ada: kesadaran bahwa makanan punya jejak, dan jejak itu bisa ditebus.
Dari Meja Makan ke Kesadaran Bersama
Di Retro Farm, keberlanjutan tidak dikemas lewat poster besar atau peringatan keras. Ia hadir lewat kebiasaan. Sisa makanan yang tidak sempat berbau karena langsung dikelola. Peternak yang terbantu karena mendapatkan pakan gratis. Unggas, ayam, hingga kambing yang ikut merasakan manfaatnya.
“Sekarang malah jadi rebutan. Mereka nggak perlu beli pakan di toko,” katanya sambil tertawa kecil.
Siklus ini juga menyentuh sektor lain. Ampas kopi, misalnya, tidak berhenti di tong sampah. Ampas tersebut dikumpulkan, difermentasi, lalu dikembalikan ke petani kopi mitra sebagai pupuk. Biji kopi yang digunakan pun dipilih dari roastery lokal dengan jarak tempuh pendek mengurangi emisi sekaligus memutar ekonomi sekitar.
“Kami ingin sirkulasi ekonomi itu jalan. Dari petani, ke roastery, ke kami, lalu kembali lagi ke petani,” jelasnya.
Perlahan, kesadaran itu menular ke pelanggan. Ketika seseorang tahu bahwa makanan yang ia pesan memiliki jejak karbon, respons yang muncul bukan penolakan, melainkan refleksi.
“Oh ternyata ada jejak karbonnya ya. Berarti aku habisin aja makananku,” katanya menirukan respons pelanggan.
Di titik ini, Retro Farm tidak sedang menjual rasa bersalah. Mereka menawarkan pilihan dan ruang belajar. Cerita Retro Farm menunjukkan bahwa transisi menuju gaya hidup rendah karbon tidak selalu datang dari kebijakan besar atau teknologi mahal. Kadang, ia tumbuh dari dapur kecil, dari sisa nasi yang tidak dibuang, dari keberanian untuk menghitung, dan dari ajakan sederhana: kalau kita makan, kita juga bertanggung jawab.
Dan mungkin, dari satu porsi makanan, satu pohon bisa tumbuh