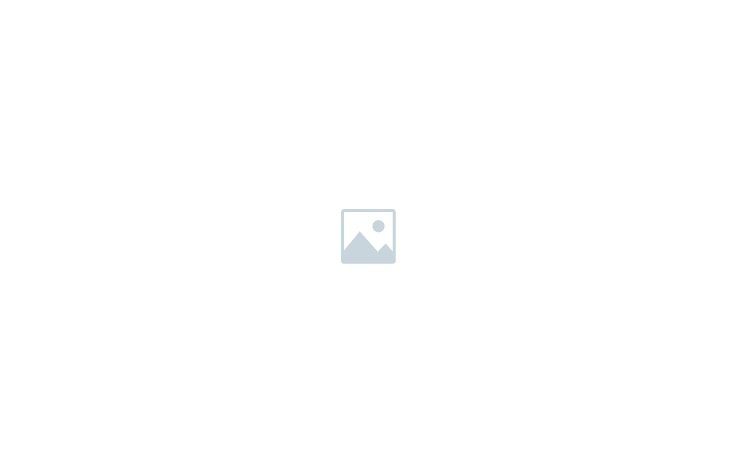Foto: Dok Pribadi/Natera
Di sebuah dapur kecil di pinggiran Kota Malang, seorang ibu menggoreng tempe mendoan yang mendesis di dalam wajan. Di balik kepulan asap yang mengepul, minyak yang ia gunakan sudah berubah warna menjadi coklat keemasan bukti ia telah melampaui panas berkali-kali. Bagi banyak rumah tangga, minyak semacam ini masih dianggap lumayan untuk sekali lagi menggoreng jajanan sore. Namun, hari itu, setelah tempe terakhir diangkat, minyak itu tidak dibuang. Ia dituang dalam botol bekas, disimpan untuk seseorang yang akan datang nanti.
Beberapa kilometer dari sana, di sebuah gudang sederhana yang baunya khas campuran minyak, mesin spinner, dan sisa tepung ayam crispy, Hari Supriyatno sedang menyusun jeriken minyak jelantah yang baru saja ia jemput. “Dulu saya keliling pakai sepeda,” ceritanya sambil tersenyum, mengingat tujuh tahun awal usahanya yang dimulai dari modal Rp500.000 pemberian temannya.
Ia datang dari warung ke warung, menerima minyak 1–2 liter tanpa banyak syarat. Yang penting, katanya, “Ambil saja dulu berapa pun adanya.”
Kini, Palim yang dulu bernama Siklus Hijau tak lagi sekadar usaha kecil mencari jelantah. Setiap hari, sekitar 400 liter minyak bekas berpindah dari dapur warga menuju gudangnya di Blimbing dan Turen, sebelum melanjutkan perjalanan ke dunia yang lebih besar. Dari rumah tangga, warung pecel lele, hotel, restoran, hingga bank sampah, semua tetes minyak itu dikumpulkan, dipisahkan, dan dikategorikan dengan teliti. Bukan karena perfeksionisme, tetapi karena di industri jelantah, kualitas adalah segalanya. Satu tetes air yang terselip bisa membuat seluruh batch ditolak pabrik.
Di mata masyarakat, minyak itu sudah mati karena terlalu keruh untuk menggoreng lagi, terlalu bau untuk disimpan. Tapi di dunia industri, jelantah adalah emas cair. Ia menjalani takdir baru menjadi biodiesel, sabun, lilin, bahkan pakan bebek pedaging. Hari mengingat, dulu ia dan keluarganya pernah membuat lilin dan sabun dari jelantah. “Bisa, kok. Cuma sulit cari partner yang bisa kemas dan pasarkan dengan harga yang masuk akal,” ujarnya, mengingat masa ketika ia mencoba membuat produk turunan tapi akhirnya memutuskan fokus ke suplai minyak mentah untuk pabrik besar.
Jejak Jenis Minyak, Dari Jernih ke Jelantah
Namun perjalanan jelantah tidak pernah sesederhana menuangkannya ke jeriken. Di baliknya ada biografi minyak yang rumit, menyangkut jenis-jenis minyak yang dipakai di dapur.
Minyak baru jernih, cerah, wangi segar baik itu minyak sawit yang paling umum, minyak kedelai, minyak bunga matahari, atau minyak padat akan perlahan berubah seiring panas. Dari kekuningan, kemudian pekat, hingga menjadi jelantah yang tidak lagi layak konsumsi.
Banyak orang tidak menyadari bahwa perubahan ini terjadi karena reaksi kimia di dalam minyak ketika ia dipanaskan berkali-kali. Sifat minyak bukan sekadar berubah warna; ia juga menyerap aroma makanan, tepung, dan air, yang kemudian memengaruhi kualitas akhirnya.
Tiga Kategori Jelantah: Ringan, Sedang, Berat
Minyak yang dipakai berulang berkali-kali dapat menghasilkan senyawa berbahaya seperti radikal bebas dan akrilamida. Karena itu, pengepul seperti Hari mengelompokkan minyak berdasarkan tingkat kerusakan dan kontaminasi. Ada minyak ringan yaitu kuning kecokelatan, masih relatif jernih, sedangkan minyak sedang itu lebih gelap, banyak sedimen dan aroma kuat. Dan minyak berat itu hitam pekat, bau gosong dominan, kental, dan penuh kotoran. Setiap kategori memiliki harga, risiko, dan tata kelola berbeda. Tidak semua minyak diterima pabrik biodiesel terutama jika sudah terlalu rusak atau tercampur bahan lain.
Menakar Kualitas: Standar Ketat Industri Jelantah
Di sinilah kualitas menjadi penentu nasib akhir minyak. Bagi pabrik biodiesel, kualitas jelantah diukur lebih dari sekadar warna.
Ada beberapa parameter yang memengaruhi kelayakan kadar air, kandungan kotoran, dan kemungkinan kontaminasi solar atau oli.
“Kelihatan kok kalau kecampur solar atau oli,” ujar Hari sambil menunjukkan contoh jelantah yang ia periksa. Tanpa alat laboratorium sekalipun, pengalaman membuatnya bisa membedakan minyak yang layak dan yang harus dipisahkan.
Ironisnya, di dapur rumah, minyak yang sudah sangat gelap masih dipakai untuk gorengan terakhir. Namun di gudang Palim, minyak tersebut berubah status: dari limbah yang dianggap menjijikkan, ia naik kelas menjadi komoditas industri bernilai tinggi.
Minyak yang terkumpul akan dimasukkan ke tandon besar, lalu ditarik dengan truk pabrik eksportir. Dari Malang, ia menempuh perjalanan menuju Surabaya, kemudian dimuat ke peti kemas, dan akhirnya diberangkatkan ke Belanda tempat biodiesel diproduksi dan siap kembali ke Indonesia sebagai energi terbarukan.
Ada ironi lembut yang terasa: minyak bekas gorengan tempe dari rumah-rumah kecil di Malang tiba-tiba menjadi bagian dari rantai energi global. Tapi di balik cerita besar itu, keberlanjutan tetap bergantung pada hal-hal kecil: kesediaan warga untuk tidak membuang minyak ke wastafel, kesabaran Hari menjemput minyak 1–2 liter tanpa minimal, hingga edukasi yang ia lakukan dari satu pertemuan PKK ke pertemuan lainnya.
Setiap sesi sosialisasi bahkan dilengkapi doorprize, karena tidak semua orang percaya bahwa jelantah benar-benar dipakai untuk biodiesel, bukan dioplos kembali menjadi minyak curah murah. “Dulu banyak yang nggak percaya. Makanya kita sosialisasi terus, bawa surat dari pabrik, jelasin prosesnya,” tambahnya.
Di balik cerita teknis tentang kualitas minyak, bisnis jelantah juga bersinggungan dengan dinamika sosial. Ada pengepul yang tidak mau terekspos media karena takut pajak. Ada persaingan dengan program penukaran minyak Pertamina yang dinilai kurang praktis. Ada juga fluktuasi harga yang dipengaruhi kebijakan pemerintah dan musim ekspor. Semua itu membuat perjalanan setetes minyak tak hanya berliku, tetapi juga sangat manusiawi.
Menjelang sore, Hari menutup gudang sambil meletakkan jeriken terakhir di sudut. Ketika ditanya apa harapannya untuk usaha ini, jawabannya sederhana: agar orang lebih sadar bahwa minyak bukan sekadar benda sekali pakai. Bahwa limbah dari dapur kecil bisa punya dampak besar, baik bagi lingkungan maupun ekonomi. “Yang dulu dianggap nggak berguna, ternyata bisa jadi cuan,” katanya pelan, sebelum kemudian menambahkan, “Dan yang penting, menyelamatkan lingkungan”.
Di tangan Palim dan ribuan warga yang mulai peduli, setetes minyak yang dulu dibuang sembarangan kini punya masa depan. Dari wajan panas, ke botol bekas, ke tandon besar, hingga ke kapal ekspor minyak itu terus bergerak. Meninggalkan jejak kecil di dapur, dan jejak besar di bumi.