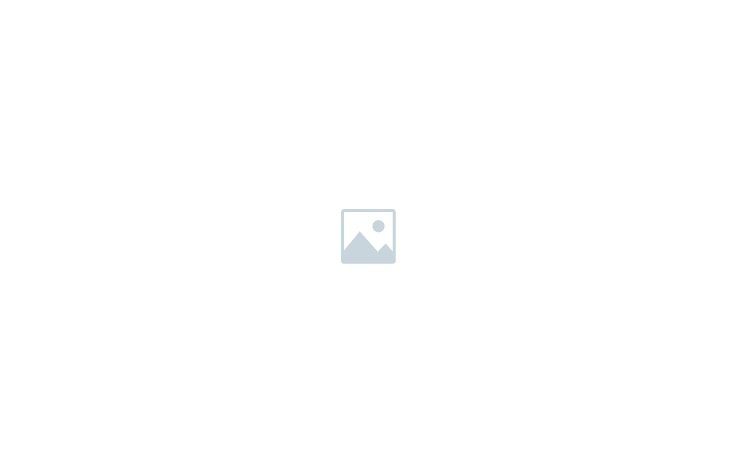Setiap kali kita melihat konten thrift haul atau menemukan jaket vintage unik dengan harga murah, rasa ingin membeli kerap muncul begitu saja. Seolah pilihan itu otomatis ramah lingkungan dan lebih bertanggung jawab dibanding membeli pakaian baru.
Ketertarikan semacam ini barangkali juga Naters rasakan, bukan? Namun, di balik rak penuh pakaian bekas dan narasi keberlanjutan, ada pertanyaan yang perlu kita ajukan bersama dengan jujur dan perlahan.
Apakah thrifting benar-benar membantu bumi, atau justru menyembunyikan cerita konsumsi lama dengan wajah yang lebih ramah?
Ketika Pakaian Menjadi Sampah Terlalu Cepat
Industri fashion terus bergerak cepat, sementara umur pakaian justru semakin pendek. Banyak baju berakhir di lemari, lalu keluar lagi tanpa sempat benar-benar menemani keseharian pemiliknya.

Foto : Dok Pribadi/Natera
“Ketika kalian itu udah gak mau sebuah barang, mungkin di mata kalian barang itu tuh sampah. Tapi di mata orang lain mungkin itu treasure.” Ujar Jessica Laihad, CEO dan Co-Founder Triftin, mengingatkan soal cara kita memandang pakaian dalam Webinar GreenSkill ID.
Thrifting hadir sebagai jalan kedua bagi pakaian yang tersingkir sebelum waktunya. Ia memberi cerita baru pada barang lama, sekaligus membuka ruang berbagi antar konsumen.
Namun, niat baik ini tentunya tidak hidup di ruang hampa. Ia berdampingan dengan sistem fashion global yang rakus sumber daya dan minim jeda refleksi.
Menurut United Nations Environment Programme, industri fashion menghabiskan 93 miliar meter kubik air setiap tahun. Sekitar 20 persen limbah air industri global juga berasal dari proses pencelupan dan pengolahan kain.
Thrifting yang Kini Penuh Cerita
Bagi banyak anak muda, thrifting bukan sekadar alternatif murah. Ia menjelma ruang eksplorasi gaya, identitas, dan cerita personal yang tidak mudah ditemukan di toko ritel besar.
“Malah keren kok, kayak menurut aku thrifting tuh kamu menemukan barang-barang unik deh. Pokoknya yang kamu gak akan kembaran deh pokoknya sama orang-orang.” Jessica melihat sisi itu sebagai kekuatan.
Keunikan itu membuat thrifting terasa lebih personal dan manusiawi. Pakaian tidak lagi sekadar produk massal, tetapi artefak dengan sejarah.
Namun, di titik ini pula godaan muncul. Murah, unik, dan mudah ditemukan bisa mendorong kita membeli lebih banyak dari yang benar-benar kita butuhkan.
Padahal, menurut UNEP, industri fashion menyumbang sekitar 10 persen emisi karbon global tahunan. Angka ini berpotensi melonjak lebih dari 50 persen pada 2030 jika pola konsumsi tidak berubah.
Saat Narasi Hijau Thrifting Menjadi Dorongan Belanja
Menurut kacamata Natera, konsep ramah lingkungan dari thrifting tidak selalu membawa dampak positif. Harga terjangkau sering memicu perilaku belanja berlebihan tanpa perencanaan yang matang.
Banyak orang membeli pakaian bekas karena murah, bukan karena perlu. Tidak sedikit yang akhirnya menumpuk barang yang jarang, bahkan tidak pernah, mereka pakai.
Fenomena thrift shopping haul ikut memperkuat pola ini. Influencer membongkar belanjaan mereka, lalu audiens terdorong meniru, bukan merefleksikan.
Alih-alih mengurangi limbah tekstil, pola ini justru berpotensi menciptakan siklus baru pembuangan pakaian. Thrifting pun berisiko mengulang masalah lama dengan kemasan berbeda.
Kembali ke Inti Ekonomi Sirkular
“ada beberapa brand-brand yang aku juga try to promote supaya orang-orang tau yang sustainable apa aja gitu.” tekan Jessica pada pentingnya memahami fashion berkelanjutan secara utuh.
Dalam catatan diskusi yang ia sampaikan dalam webinar GreenSkill ID, keberlanjutan bukan sekadar soal bekas atau baru. Ia tentang produk yang dirancang cermat agar bisa digunakan ulang, diperbaiki, terurai alami, dan tetap indah.
Thrifting bisa menjadi bagian dari ekonomi sirkular, tetapi hanya jika kita menjaga perilaku konsumsi. Tanpa kontrol, ia mudah tergelincir menjadi konsumsi impulsif berkedok hijau.
Mungkin, tantangan terbesarnya bukan pada pakaian yang kita beli. Tantangan itu ada pada keberanian kita untuk berhenti, memilah, dan bertanya sebelum membawa pulang satu potong lagi.
Karena pada akhirnya, bumi tidak hanya butuh pilihan yang terlihat ramah. Bumi butuh manusia yang mau cukup.